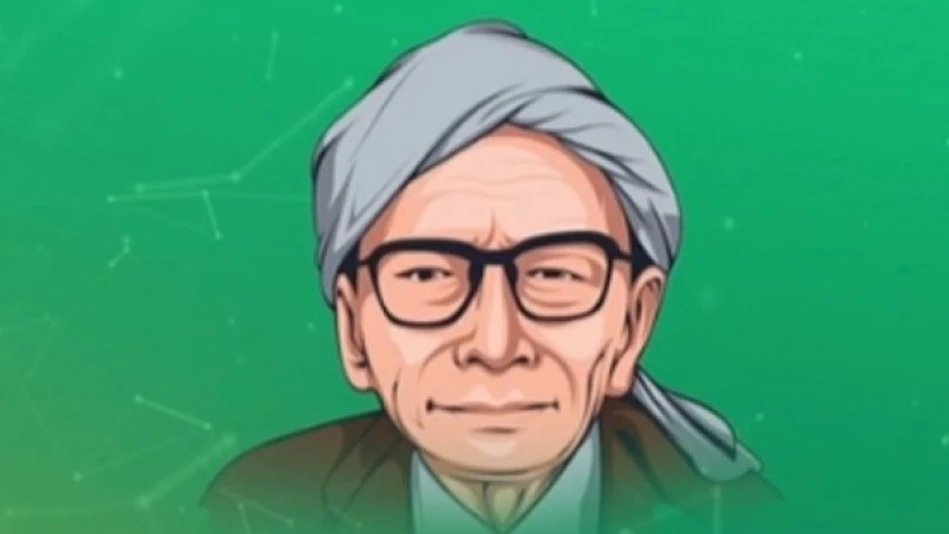KH. Wahab Hasbullah adalah sedikit dari tokoh besar yang lahir dari rahim pesantren. Beliau melintasi zaman yang penuh dengan peristiwa bersejarah yang membicarakan proses berdirinya negara Indonesia.
Dimulai dari era kolonialisme Jepang dan Belanda yang mencabik-cabik serta menyesap darah masyarakat pribumi, kemudian era Wahabisme (yaitu paham puritan yang ingin mencerabut tradisi lokal dari akarnya), hingga kemudian pada era Komunisme (yang menjelma menjadi ancaman serius bagi Indonesia yang baru saja menghirup udara kemerdekaan), dan masa Orde Lama.
Dimana disintegrasi bangsa bermunculan, tidak sedikit terjadi konflik ideologis yang berpotensi memecah belah persatuan Indonesia, misalnya Pemberontakan PKI Madiun (1948 dan 1965), Pemberontakan DI/TII Jawa barat (1948-1961), Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Permesta di Sulawesi pada tahun 1950-an.Hebatnya, dalam setiap momen bersejarah tersebut Mbah Wahab selalu tampil menjadi playmaker, keterlibatan Mbah Wahab dalam setiap proses historis di atas membuatnya dikenal bukan hanya sebagai kiai (ulama), tetapi juga sebagai aktivis pergerakan, dan politikus papan atas.

Kontrisbusi pertama Mbah Wahab terhadap praktik kolonialisme dapat dilihat dari pandangan beliau yang mengatakan bahwa kolonialisme termasuk tindakan ghasab yaitu upaya menguasai hak orang lain tanpa hak (al-istîlâ’ ‘ala haqq al-ghair bi lâ haqq).
Untuk merebut kembali hak yang telah dirampas tersebut, Mbah Wahab berupaya membangun kesadaran nasional dengan meniupkan spirit keagamaan di dalamnya melalui slogan hubb al-watan min al-îmân (cinta tanah air adalah manifestasi iman).
Kontribusi kedua, menjelang akhir tahun 1950, gerakan separatis-radikal baik berbasis agama ataupun sekulerisme muncul sebagai ancaman keamanan nasional. Mbah Wahab dengan lantang menolak segala bentuk radikalisme, baik radikalisme agama ataupun radikalisme sekuler.
Menurutnya, radikalisme agama dapat mencederai kemaslahatan berbangsa dan bernegara, sedangkan radikalisme sekuler dapat mencederai kemaslahatan agama. Karena menurut Mbah Wahab tindakan seorang imam/pemimpin atas komunitas yang dipimpinnya harus didasarkan pada pertimbangan maslahat (t’arruf al-imâm ‘ala al-ra‘iyyah manúttun bi al-maslahah). Tulis Miftakhul dalam jurnal “Pemikiran Mbah Wahab Hasbulah Perspektif Fikih”, halaman 191.
Kontribusi ketiga, memelihara budaya lokal. Gerakan Mbah Wahab tersebut dapat dilihat ketika situasi bangsa Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda, dimana pengaruh paham Wahabi mulai masuk ke Indonesia dengan kedok gerakan pembaruan Islam.
Sebagai respon dari Gerakan Wahabisme mbah Wahab melawanya dengan kaidah (al-‘adat muhakkamah), bahwa kebiasan lokal selama tidak menyimpang dari prinsip syariat bisa diakomodir sebagai salah satu sumber inspirasi hukum. Menurutnya menjadi muslim yang baik tidak harus menanggalkan tradisi.
Beberapa pemikiran Mbah Wahab tentang menggabungan budaya lokal misalnya, tentang konsep “politik keris-keras”, “persatuan kusiriyah”, “halal bi halal”, “diplomasi cancut taliwondo”, dan “sosialisme Indonesia” menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang kuat dalam menjaga tradisi sehingga memiliki pemikiran yang indigenos, khas Nusantara. Begitu tulis Miftakhul Arif dalam jurnal yang sama pada halaman 205.
Corak pemikiran serta pengambilan keputusan Mbah Wahab pada konteks kenegaraan semuanya dilandasi oleh pemikiran fikih. Spirit keilmuan agama yang moderat, nyatanya berhasil menciptakan peradaban yang maha dahsyat tanpa melukai ataupun menghardik sesama putra bangsa.
Semoga semangat ini dapat diteruskan oleh warga Nahdiyyin serta menegaskan bahwa ilmu agama tidak hanya menyoal boleh/tidak namun sebagai lokomotif untuk mebawa dunia menuju peradaban yang maju, harmonis dan beradab.
Oleh: Ahmad Safarudin (Pengurus PB PMII dan Aktivis NU DKI Jakarta)