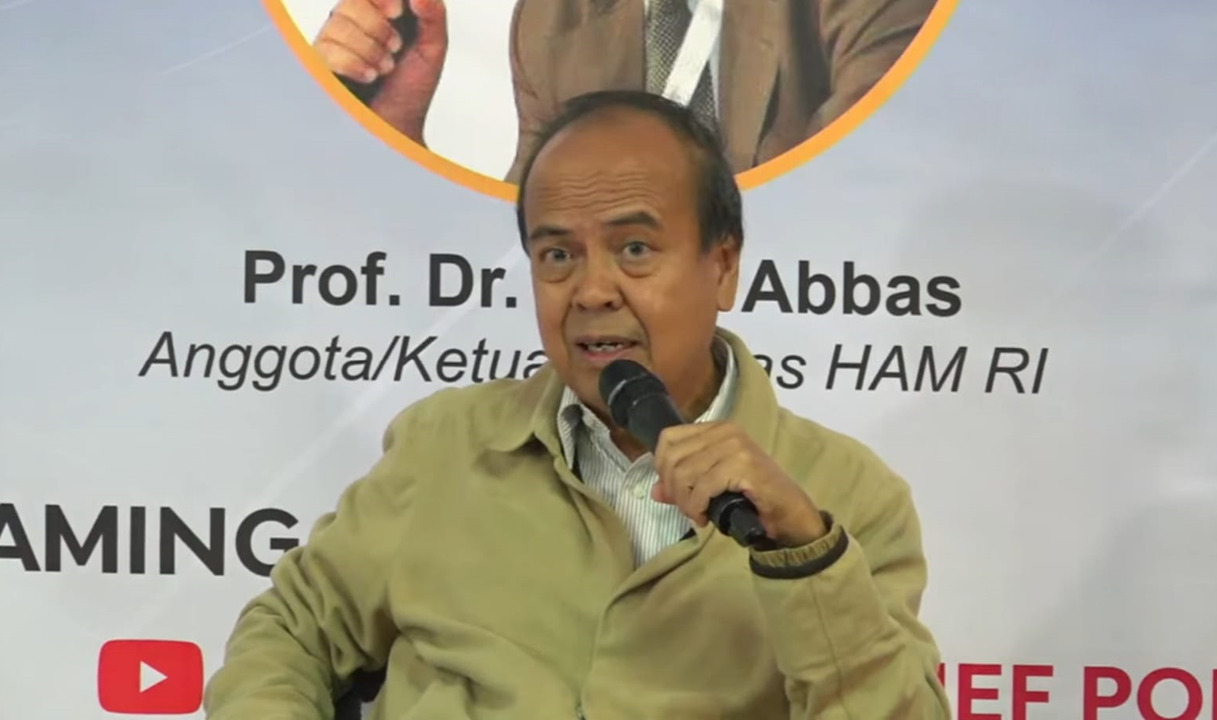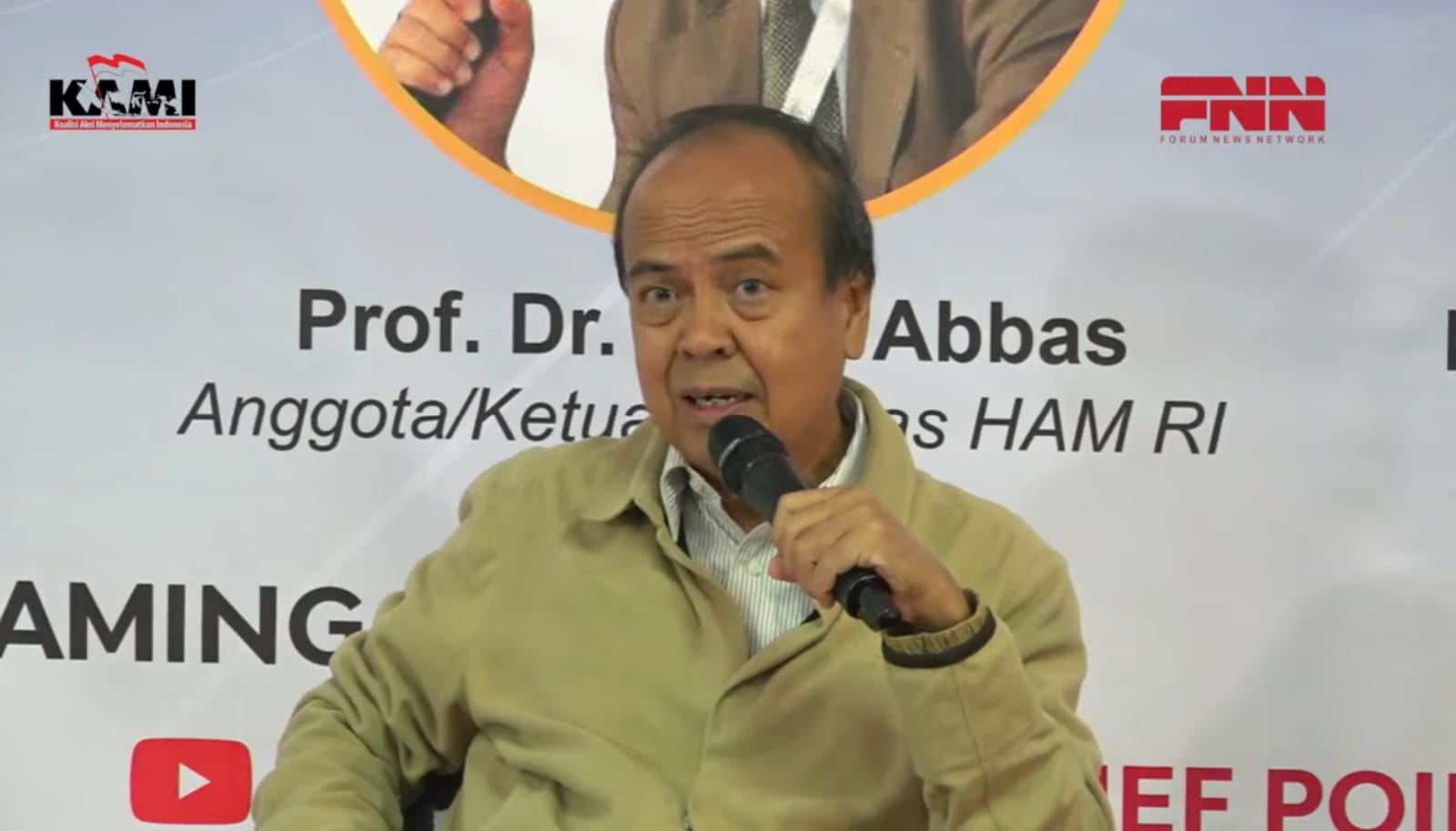Oleh : Prof. Dr. Hafid Abbas (Ketua Senat Universitas Negeri Jakarta)
Akhir-akhir ini, publik ramai menyoroti polarisasi pro-kontra terhadap sistem pelaksanaan Pemilu 2024 secara proporsional terbuka seperti yang sudah berlangsung sebanyak empat kali sejak era Reformasi. Dengan sistem itu, banyak pihak yang mengagumi bahwa Indonesia telah berhasil telah menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Sebaliknya, banyak pula pihak yang menolak sistem terbuka, dan berpandangan bahwa sistem proporsional tertutup adalah pilihan yang lebih sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanat reformasi yang telah digulirkan sejak
Polarisasi itu terlihat mengemuka ke publik pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK) pada 8 Maret lalu dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pihak yang menolak sistem terbuka berpandangan bahwa dengan berlakunya Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan.
Bahkan dinilai pergeseran hak untuk menempatkan kandidat dari partai politik kepada kuantitas suara terbanyak ini jelas bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2), (3) dan Pasal 28D ayat (1) UU NRI 1945.
Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU 1945 telah menegaskan kedaulatan yang berada di tangan rakyat itu tidaklah dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia melainkan dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh UUD yakni oleh ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 dilakukan oleh partai politik melalui kepersertaannya di pemilu untuk memilih DPR, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden.
Sistem proporsional terbuka adalah sistem Pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil-wakilnya. Sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politiknya saja.
Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nomor urut ditentukan oleh partai politik. Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Setelah itu, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Refleksi
Sejak Indonesia memilih jalan demokrasi di penghujung abad ke-20, dengan pelaksanaan pemilu secara proporsional terbuka berbiaya mahal kelihatannya telah menghasilkan corak kepemimpinan di pusat dan daerah sesuai dengan Hukum Darwin, “survival of the fittest,” yang kuatlah yang pasti menang dan yang lemah akan
Sebagai ilustrasi, hasil penelitian Tempo satu dekade silam, menunjukkan bahwa biaya calon anggota DPR RI dapat mencapai Rp 6 miliar (Tempo, 22/4/2013). KPK telah mengungkapkan pula bahwa biaya yang harus dikeluarkan seseorang agar terpilih menjadi Kepala Daerah (Bupati, Walikota atau Gubernur) bervariasi antara Rp 20-100 miliar atau rata-rata Rp 60 miliar (Kompas, 23/7/2020).
Dengan biaya politik sebesar itu tentu hanya akan menjaring orang-orang yang berduit untuk mendominasi perolehan kursi di legislatif atau pun di eksekutif di pusat dan daerah.
Di sisi lain gaji pejabat Indonesia 2019-2024, mulai dari Bupati hingga Presiden, terlihat amat rendah. Jika seorang Bupati berpendapatan hanya dari gaji pokok dan tunjangan resminya sebesar Rp 5,88 juta sebulan (gajimu.com), maka untuk mengembalikan modalnya, ia harus bekerja sebagai Bupati selama 170-171 tahun.
Rentetan sisi gelap dari Pemilu berbiaya mahal itu, dampaknya antara lain: Pertama, para wakil rakyat, dan para pejabat pusat dan daerah yang dipilih dengan sistem terbuka itu (elit politik), tentu tidak akan mengabdi untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat. Sebab, mereka sudah tersandera oleh beban untuk mengembalikan biaya politiknya. Cara mudah untuk mengembalikan biaya politik itu, adalah dengan merangkul korporasi dengan memberinya hak penguasaan lahan, tambang, dan sumber-sumber daya alam (SDA) setempat, dsb.
Karenanya, jika dihitung jumlah pemberian izin konsesi lahan untuk penguasaan SDA oleh pemerintah pusat dan daerah kepada korporasi, misalnya di Sulawesi Tenggara ternyata luasnya sudah melebihi seluruh luas daratan provinsi itu sendiri. Ini juga terjadi di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan provinsi-provinsi lainnya di tanah air (Kompas,21/05/2018).
Bahkan, terdapat 35 juta hektar tanah yang dikuasai oleh beberapa korporasi besar, dan dan terdapat juga 14,6 juta hektar lahan sawit sehingga tanah seluas sekitar 50 juta hektar atau 758 kali luas Jakarta, hanya dikuasai oleh beberapa kelompok pengusaha (Kompas, 15/03/2018).
Kedua, jika masyarakat memprotes lahirnya satu kebijakan diskriminatif dari elit politik, karena lahannya sebagai sumber kehidupannya harus diberikan ke pemilik modal, polisi hadir untuk meredam setiap gejolak yang timbul untuk mengamankan konspirasi antara korporasi dengan elit politik hasil pemilu. Akibatnya, kekerasan dan intimidasi yang dialami masyarakat semakin meningkat.
KontraS mencatat dalam periode Juli 2021 hingga Juni 2022, terdapat 677 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kekerasan itu didominasi penggunaan senjata api sebanyak 456 kasus yang telah menyebabkan 59 orang meninggal, 928 luka-luka, dan 1.240 ditangkap secara sewenang-wenang. Kasus terjadi di tingkat Polsek sebanyak 121, dan di Polda sebanyak 77 kasus (Kompas.com, 30/06/2022).
Ketiga, jika masyarakat menempuh jalur hukum atas perampasan hak-haknya dapat dipastikan mereka akan kalah. Sepanjang 2014, sebagai contoh, Komnas HAM RI menerima 6967 pengaduan masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah tanah air. Mereka mengadukan: polisi 35,6% (2483 kasus), korporasi 1590 kasus(22,8%), Pemda 1270 kasus (18,3%), peradilan dan kejaksaan 836 (12%), dan selebihnya lain-lain. Data ini menunjukkan bahwa 88,7% kasus aktor utamanya adalah polisi, korporasi dan Pemda.
Hingga saat ini, potret kelam ini belum berubah. Institusi kepolisian tetap berada pada pososi tertinggi yang diadukan oleh masyarakat.
Selanjutnya, substansi pengaduan itu memperlihatkan 43,2% (3011 kasus) terkait dengan hilangnya hak masyarakat memperoleh keadilan; 42,5% (2959 kasus) menyatakan hilangnya hak mereka atas kesejahteraan karena tanah mereka sebagai sumber kehidupannya telah dirampas; dan hilangnya rasa aman warga sebesar 12,5% (871 kasus).
Data ini menunjukkan bahwa 98,2% keresahan masyarakat terkait dengan hilangnya ketiga hak dasar itu.
Indonesia Terancam Bubar
Jika corak demokrasi dengan sistem Pemilu secara proporsional terbuka terus dipertahankan kelihatannya Indonesia akan terancam bubar karena hanya akan memperbesar gurita oligarki. Kini jurang kaya-miskin di negeri ini terlihat ke empat terburukt di dunia. Bahkan, Oxfam menyebutkan kekayaan kolektif empat orang terkaya di Indonesia, sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin (2017). Bahkan kekayaan 50 WNI kelas atas menguasai lebih 48% total GDP atau 72% dari total APBN 2021 yang mencapai 2750 triliun rupiah (Jakarta Post, 18/12/2020).
Bank Dunia memperkirakan Indonesia pada akhirnya akan bubar. Dalam publikasinya, Indonesia Rising Divide (2016, hal.28), terdapat empat sumber penyebab pecahnya NKRI.
Pertama, adanya ketidaksamaam pemberian kesempatan kepada setiap warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Misalnya, ada pihak diberi kesempatan menguasai jutaan hektar lahan, sementara pada 2016 orang miskin di DKI Jakarta, misalnya, digusur sebanyak 193 kali setahun (Tempo, 13/04/2017).
Kedua, kelompok masyarakat miskin semakin tertinggal karena tidak memiliki pendidikan berkualitas untuk bersaing dengan kelas masyarakat atas di sektor ekonomi modern. Mereka hanya dapat diserap di sektor informal yang berupah amat rendah.
Ketiga, kosentrasi peredaran uang dan modal di negeri ini hanya berputar di beberapa orang atau beberapa perusahaan. Misalnya, terdapat 56,5 juta UMKM yang tidak tersentuh dengan bantuan perbankkan (Data BUMN, 2019).
Keempat, orang miskin ini tidak memiliki tabungan untuk membiayai pendidikan anaknya dan juga tidak memiliki tabungan untuk biaya kesehatannya di hari tuanya.
Dengan gambaran itu, pandangan Prabowo Subianto kelihatannya cukup beralasan jika dikatakan Indonesia sudah tidak ada lagi pada 2030 (BBC, 24/03/2018).
Semoga ke depan, pelaksanaan Pemilu 2024 secara proporsional terbuka dapat dihindari karena telah secara nyata menghasilkan pemimpin politik di pusat dan daerah yang telah membawa negeri ini semakin menjauh dari cita-cita proklamasi dan amanat reformasi 1998. Bukankah keledai saja tidak akan pernah terjatuh pada lubang yang sama untuk kedua kalinya.
Istanbul, 13 Maret 2023